Lisabona Rahman: Perempuan, Pemikiran dan Pencatatan Sejarah
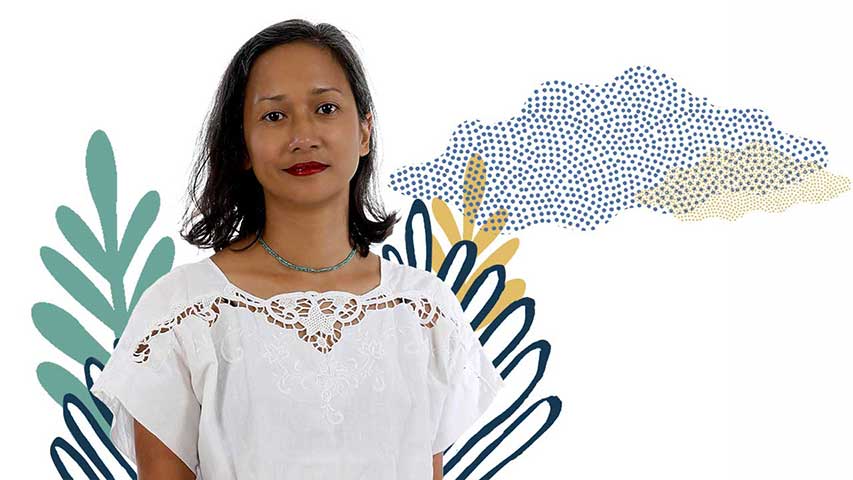
Lisabona Rahman, dikenal sebagai salah satu penggiat film dan sejarah film, dan pada akhir-akhir ini menjadi aktivis pengarsipan film. Semenjak kecil hidupnya berpindah-pindah, lahir di Lisbon, Portugal pada tahun 1978 ia sekeluarga bermukim di Kuwait, Mesir, dan banyak negara lainnya. Absen dalam menikmati film nasional, yang hanya dijumpai via kaset video, pada tahun 1993-2006 Lisabona mulai menyimak perkembangan film Indonesia langsung di Indonesia. “Awalnya karena saya senang menjadi sukarelawan di Pusat Kebudayaan, saya jadi sadar bahwa produksi film alternatif tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga secara teratur memproduksi film ini. Ada yang membuat film pendek, ada yang membuat film dokumenter,” jelasnya. Menurut Lisa film-film Indonesia alternatif seperti berada pada dunia yang tak terlihat, namun hadir secara konstan. Karena tidak “hadir” dalam arus utama, Lisabona merasa bahwa Indonesia memiliki realitas alternatif yang sebenarnya sangat penting, menurutnya pembuat-pembuat film alternatif inilah yang menghidupkan kembali film Indonesia. Keterlibatannya dalam dunia film di Indonesia digambarkannya sebagai dinamika ‘terseret arus kala gerakan itu tumbuh, membesar, terlibat di dalamnya, hingga terbawa sampai sekarang’.
Lisa mengenang film alternatif yang sangat berpengaruh untuk untuknya adalah yang disaksikannya saat ia berumur 16 tahun, film yang berjudul “The Lover” (Kekasih) berdasarkan novel autobiografis karya Marguerite Duras yang disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud. Film ini berkesan karena merupakan pertama kalinya Lisa menonton film non-Hollywood dengan cerita yang kompleks. Perempuan Perancis berusia remaja yang bermukim di Saigon, Vietnam dan bersekolah di Sekolah Katolik khusus orang asing, dan berpacaran dengan orang Cina-Vietnam yang kaya raya. Film ini membahas mengenai topik perempuan akil-baligh (dari remaja menuju dewasa-red), kolonialisme, dan keluarga. Cerita film ini menjadi berpengaruh karena membuka pikirannya dan terus menerus mencari novel karya Marguerite Duras. “Orang ini aneh banget, dia menulis novel, novelnya dibuat film, kemudian dia menulis novel lagi yang membicarakan mengenai filmnya. Karena dia adalah orang teater dan sutradara teater, dia sangat kritis dan terus menerus melihat karyanya lagi, di mana karyanya berdialog dengan karya orang lain, dan dialognya menjadi karya sendiri, seperti penyihir yang ingin memegang kendali utama. Untuk saya ini menarik banget. Wah!” tutur Lisabona panjang lebar. Lisa kemudian membahas latar belakang Marguerite Duras dan bagaimana ia melihat karya Marguerite dengan realitas masyarakat Indonesia. “Marguerite adalah orang Perancis yang besar di Vietnam, karyanya mencerminkan pandangannya mengenai hidup koloni, sementara saya yang membaca mewarisi kesadaaran-kesadaran tentang masyarakat post-colonial. Pendapat-pendapat mengenai, ‘penjajahan Belanda itu harus dimusnahkan’ dan sebagainya. Tapi dari Marguerite Duras ini saya melihat aspek-aspek penjajahan secara personal, termasuk yang sangat pahit, namun orisinil. Mengenai kolonialisme, keluar dari kotak bahwa penjajahan hanya melulu perjuangan dan nasionalisme,” jelas Lisabona mengenai perempuan yang menjadi inspirasinya. Ia mengakui secara tidak sadar, sejak remaja hingga kini selalu kembali ke karya-karya Marguerite Duras.
Dalam seni dan budaya, Lisabona merefleksikan pengalamannya dan keputusan-keputusannya yang membawanya hingga pilihan karirnya sekarang ‘berkeliling ke mana-mana’ sebagai tidak lurus. Walaupun ia tidak menyesali keputusannya dan pengalamannya, ia mengakui bahwa terlambat dalam menyadari pilihan pilihan karir dan kesempatan (sumber daya) yang tersedia sangat berpengaruh dari bagaimana masyarakat menilai umur dan gender. Sebagai perempuan, pilihan-pilihan yang mereka buat sebagai karir, seringkali terlambat. Hal ini dikarenakan pilihan-pilihan tersebut tidak selalu gampang untuk dibuat, banyak hal yang harus dikorbankan untuk pilihan tersebut. Upaya untuk membuat perempuan tetap percaya bahwa pilihan-pilihan ini mungkin, disadari sulit di Indonesia. Lisabona menimbang mengenai sumber daya yang tersedia untuk perempuan serta dianggap umum dan jumlah perempuan tidak seimbang, ”Akhirnya profesi dan dana masuknya ke laki-laki lagi, laki-laki lagi. Contohnya seperti ini, kamu seniman perempuan dan memutuskan untuk punya anak. Namun walaupun punya anak kamu tetap punya ekspresi kreatif dan bisa berkarya, tapi uang kamu tidak cukup untuk bayar pengasuh anak. Sementara sistem bantuan (orang tua/ saudara) kamu tidak ada, karena, misalnya, kamu perantau. Sehingga kamu harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus anak kamu, tak bisa lagi ada waktu untuk berkarya. Kita perlu cara pendanaan yang mengerti apa artinya hidup menjadi perempuan, sehingga bisa jadi proses karyanya tidak butuh bantuan dana, namun bantuan dana diperlukan karena untuk bisa berkarya dana butuh membayar pengasuh anak.”
Menurut Lisabona, akhirnya dalam sejarah seni dan kebudayaan menjadi sedikit sekali perempuan Indonesia di ranah ini. Lisabona mencontohkan Prof. Toeti Heraty, sebagai pemikir kebudayaan, namun dibandingkan dengan rekan-rekan sejawatnya yang laki-laki, jumlahnya kalah jauh. Akhirnya teks-teks kebudayaan sebagian besar diproduksi laki-laki dan dijadikan acuan budaya dan seni. Lisabona melihat sebetulnya banyak perempuan berkarya, berpikir, dan berekspresi. “Pertanyaannya menjadi, apakah karya-karya mereka, pikiran, dan ekspresi mereka tidak dianggap? Mengapa tidak terekam? Akhirnya saya menyadari bahwa untuk bisa direkam, dan dianggap, perlu infrastrukturnya sendiri. Salah satunya adalah perlunya uang atau dana,” ujarnya.
Saat ditanya apakah skema pendanaan untuk seni rupa yang ada sebelumnya kurang memadai, Lisa menjawab dari segi jumlah dan jenisnya skema ini masih kurang. “Inisiatif tidak bisa satu atau dua, harus banyak. Sementara cara pendanaan yang mengerti apa artinya hidup sebagai perempuan, tidak ada.” Selain dana, Lisabona mengemukaan pentingnya wacana betapa pentingnya ekspresi seni perempuan. “Misalnya, kamu datang dari keluarga yang canggih memasak, punya banyak resep yang turun dari buyut, ke nenek, ibu, sampai ke kamu. Apabila kamu yang masak, jadinya masakan rumahan, tapi apabila resep ini dibagikan kepada koki terkenal, resepnya bisa jadi seni kuliner. Sehingga masalahnya kembali ke siapa yang mau kita anggap? Wacana yang dominan di masyarakat sekarang buta terhadap pengetahuan alternatif di kalangan perempuan dan ekspresi-ekspresinya dalam kebudayaan dan seni. Contohnya tenun, banyak yang menganggap tenun itu kerajinan dan bukan seni. Kita terhalang wacana pencipta dan pemilik hak cipta yang individualistis dan berorientasi laki-laki, sehingga perempuan-perempuan jadi tak terlihat,” ujarnya.
Sumber: Lisabona Rahman. Wawancara oleh Ayu Larasati, Jakarta, 4 November 2017. Disunting oleh Siska Doviana.